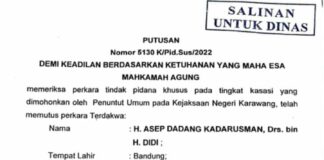Jakarta, SUARABUANA.com 23 Desember 2025 — Diskusi publik yang disiarkan melalui kanal TikTok Bang Arthon mengangkat isu krisis lingkungan yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh sebagai persoalan struktural dalam tata kelola sumber daya alam Indonesia. Diskusi ini menegaskan bahwa tragedi ekologis yang berulang tidak dapat dilepaskan dari relasi kuasa antara pemodal besar dan negara.
Diskusi publik tersebut menghadirkan Guntur Nara Persada, Pemimpin Redaksi Jawa TV Pos, dan Tarmin Realistica, seorang sosiolog. Acara berlangsung pada pukul 20.00 WIB hingga 21.20 WIB dan diikuti oleh 589 peserta, yang terdiri dari mahasiswa Universitas Nasional serta masyarakat umum.
Dalam pemaparannya, Guntur Nara Persada menegaskan bahwa krisis ekologis di wilayah Sumatera tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kegagalan teknis pengelolaan lingkungan. Menurutnya, kerusakan lingkungan merupakan dampak langsung dari relasi kuasa antara oligarki pemodal dan negara.
Ia menjelaskan bahwa industri sawit menjadi arena utama bertemunya kepentingan ekonomi dan politik. Segelintir elite pemilik modal menguasai lahan, memengaruhi kebijakan, serta memperoleh legitimasi negara, sehingga kerusakan ekologis berlangsung secara sistemik dan berulang. Negara dinilai tidak berada pada posisi netral, melainkan berfungsi sebagai penjamin akumulasi modal melalui regulasi, perizinan, dan narasi pembangunan.
Menurut Guntur, kekuasaan ekonomi di Indonesia terkonsentrasi pada kelompok kecil pemodal besar yang memiliki kemampuan untuk mengarahkan kebijakan publik sesuai kepentingannya. Dalam konteks industri sawit, konglomerasi besar menguasai aset strategis sekaligus membangun jejaring politik yang kuat. Relasi ini melahirkan apa yang ia sebut sebagai “politik pembiaran”, yaitu sikap negara yang membiarkan deforestasi dan degradasi lingkungan selama aktivitas tersebut dianggap legal dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Guntur juga mengungkapkan data penyusutan hutan rawa di Indonesia yang menurun drastis, dari sekitar 96 juta hektare pada tahun 1990 menjadi 55,45 juta hektare, sebagai indikator empirik dominasi logika ekonomi atas logika ekologis.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa konflik ekologis tidak terlepas dari persoalan aktor dan akses terhadap sumber daya alam. Negara, korporasi, dan masyarakat lokal memiliki posisi kuasa yang timpang. Akses terhadap sumber daya tidak hanya ditentukan oleh kepemilikan formal, tetapi juga oleh kemampuan politik, ekonomi, dan simbolik untuk mengontrolnya.
Sementara itu, Tarmin Realistica menambahkan bahwa masyarakat lokal berada pada posisi paling lemah akibat keterbatasan modal, jaringan politik, dan legitimasi hukum. Sebaliknya, korporasi memperoleh akses luas melalui dukungan negara, sehingga deforestasi dan alih fungsi hutan menjadi praktik yang sah secara hukum, meskipun merusak secara ekologis. Kondisi ini mencerminkan ketidakadilan lingkungan, di mana risiko bencana ditanggung masyarakat, sementara keuntungan ekonomi terakumulasi pada oligarki.
Tarmin juga memaparkan bahwa oligarki di Indonesia bersifat historis dan adaptif. Sejak era pra-kemerdekaan hingga reformasi, oligarki terus bermetamorfosis mengikuti perubahan sistem politik. Dalam demokrasi elektoral, pengaruh oligarki bekerja melalui pendanaan politik, relasi informal, serta intervensi kebijakan dari balik layar. Akibatnya, demokrasi kehilangan substansi ekologis karena keputusan strategis lebih banyak ditentukan oleh kepentingan pemodal dibanding kepentingan publik.
Menanggapi pertanyaan peserta Ariq Setiawan terkait bentuk perlawanan, Guntur menegaskan bahwa resistensi terhadap oligarki tidak harus dilakukan melalui konfrontasi fisik. Mobilisasi kesadaran publik melalui pengetahuan, media, pendidikan, dan produksi wacana menjadi arena penting dalam membangun perlawanan ekologis non-kekerasan. Pertarungan opini publik, pengawasan warga (watchdog), serta transformasi kesadaran generasi muda dinilai sebagai kunci perubahan jangka panjang, meskipun reformasi struktural kerap terhambat karena negara telah terintegrasi dalam sistem oligarki.
Senada dengan hal tersebut, Tarmin menekankan pentingnya melihat persoalan ini sebagai sebuah sistem yang harus “ditulis ulang”. Ia mengutip Mahatma Gandhi bahwa kekerasan justru mencerminkan kelemahan, dan menegaskan bahwa perubahan dapat berlangsung melalui jalur evolusi maupun revolusi. Tarmin juga mengutip pemikiran Antonio Gramsci tentang intelektual organik, yakni perlunya membangun kesadaran kolektif, mengorganisasi gerakan politik dan sosial, serta melahirkan kepemimpinan baru yang mampu menata ulang aturan main. Menurutnya, tanpa kesadaran publik, tidak mungkin lahir sebuah gerakan maupun perubahan yang bermakna.
Penutup
Diskusi publik ini menyimpulkan bahwa krisis lingkungan di Indonesia merupakan manifestasi dari dominasi oligarki modal dalam politik lingkungan. Negara cenderung berperan sebagai fasilitator akumulasi kapital, bukan sebagai pelindung ekologi. Selama struktur oligarki tetap dominan, kebijakan lingkungan akan terus tunduk pada logika pertumbuhan ekonomi, dan bencana ekologis akan terus diproduksi secara sistemik.